William Saroyan
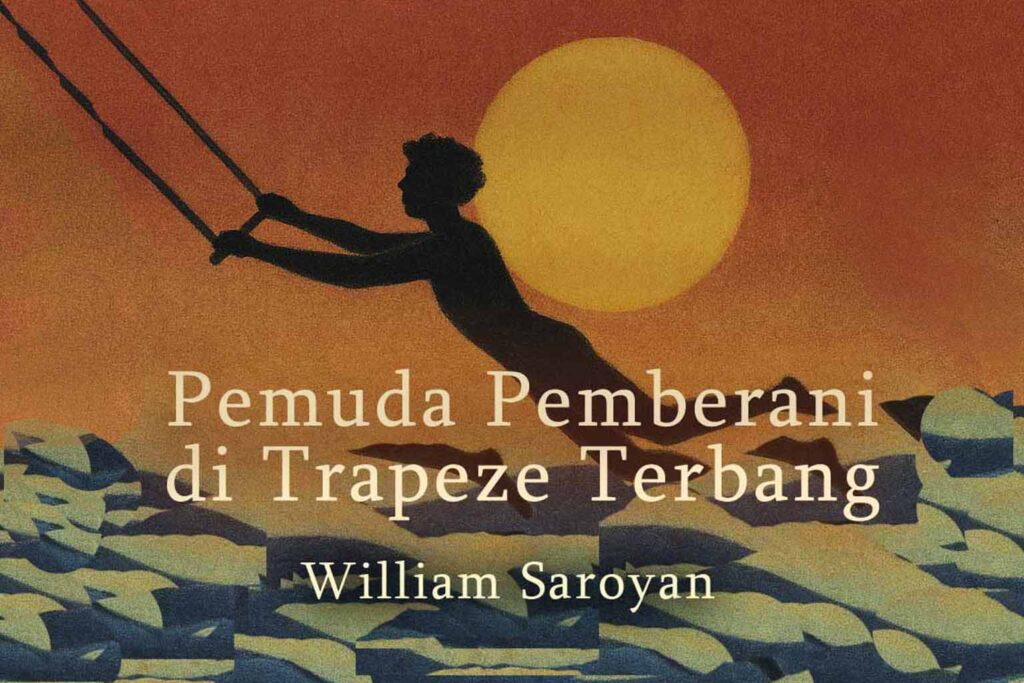
I. TIDUR
Telentang di tengah keluasan jagat raya, berlatih gelak tawa dan keriangan, sindiran, akhir dari apa saja, akhir dari Roma dan Babilonia juga, gigi terkatup, kenangan, kehangatan gunung berapi, jalanan Paris, dataran Yerikho, meluncur seperti reptil khayalan, galeri cat air, laut dan ikan-ikan bermata besar, simfoni, meja di pojokan Eiffel, jazz di gedung opera, jam weker dan tarian ketuk menuju kiamat, percakapan dengan sebatang pohon, Sungai Nil, coupe Cadillac menuju Kansas, raungan Dostoyevsky, dan matahari hitam.
Bumi ini, wajah seseorang yang pernah hidup, bentuk tanpa bobot, tangisan di atas salju, musik putih, bunga yang mengembang dua kali lipat jagat raya, awan hitam, sorot mata macan kumbang dalam kandang, ruang tanpa kematian, Tuan Eliot memanggang roti dengan lengan baju tergulung, Flaubert dan Guy de Maupassant, sajak purba tanpa kata-kata, Finlandia, matematika yang dipoles mengkilat dan licin seperti sisa sayuran di gigi, Yerusalem, jalan menuju paradoks.
Nyanyian batin manusia, bisikan licik seseorang yang tak tampak tapi samar-samar dikenal, badai di ladang jagung, permainan catur, biarkan sang ratu, sang raja, Karl Franz, Titanic hitam, Tuan Chaplin menangis, Stalin, Hitler, sekumpulan orang Yahudi, besok hari Senin, tak ada orang menari di jalanan.
Wahai, hidup yang singkat: ia telah berakhir, kenyataan telah kembali.
II. TERJAGA
Dia (yang hidup) mengenakan pakaian dan mencukur wajah, menyeringai pada bayangannya di cermin. “Benar-benar tidak tampan,” katanya. “Di mana dasiku?” (Dia hanya punya satu.) Kopi dan langit kelabu, kabut Lautan Teduh, dengung trem yang melintas, orang-orang bergerak ke kota, waktu lagi, hari lagi, prosa dan puisi. Dia melangkah cepat menuruni tangga, menyusuri ke jalan, dan berpikir tiba-tiba, Hanya dalam tidur kita tahu bahwa kita hidup. Hanya di sana, dalam kematian yang hidup itu, kita berjumpa dengan diri sendiri dan bumi yang jauh, dengan Tuhan dan para santo, dengan nama-nama para bapa, dengan substansi dari momen-momen jauh di masa lalu; di sanalah abad-abad menyatu, jagat raya menjelma atom kecil keabadian.
Dia berjalan sesadar mungkin, membuat ketukan dengan tumit sepatunya, mengamati kedangkalan jalanan dan gedung-gedung, kebenaran remeh temeh yang disebut kenyataan. Tanpa daya menghadapi itu semua, pikirannya bernyanyi: Dia melayang di udara begitu mudahnya; pemuda pemberani dengan trapeze terbangnya. Lalu dia tertawa sekuat-kuatnya. Sungguh pagi yang mengagumkan: kelabu, dingin, dan muram, pagi yang membangkitkan kekuatan batin; ah, Edgar Guest, katanya, aku sungguh merindukan musikmu.
Di selokan dia melihat sekeping uang logam, ternyata satu sen, bertahun 1923. Dia menaruh koin itu di telapak tangannya, memandanginya lama, mengenang tahun di koin dan memikirkan Lincoln, yang wajahnya tercetak di sana. Hampir tak ada yang bisa dilakukan dengan satu sen. “Aku akan membeli mobil,” pikirnya. “Aku akan mengenakan pakaian seperti lelaki genit, mengunjungi perempuan hotel, makan dan minum, dan pulang ke kesunyian. Atau aku akan memasukkan koin ini ke mesin timbang badan.”
Tak ada masalah menjadi miskin, dia tahu, tetapi sangat mengerikan menjadi orang lapar. Betapa kuatnya selera makan mereka, betapa cintanya mereka pada makanan! Perut mereka kosong. Dia teringat dia sendiri sangat memerlukan makanan. Setiap hari hanya roti, kopi, dan rokok, dan kini rotinya pun habis. Kopi tanpa roti tak bisa disebut makan malam, dan rumput taman tak bisa dimasak seperti bayam.
Kalau mau jujur, dia setengah kelaparan, tetapi masih banyak buku yang harus dia baca sebelum mati. Dia teringat pemuda Italia di rumah sakit Brooklyn, pegawai kecil bernama Mollica, yang berkata dengan nada putus asa, aku ingin melihat California sekali saja sebelum mati. Dan dia berpikir sungguh-sungguh, “Setidaknya aku harus membaca Hamlet sekali lagi; atau mungkin Huckleberry Finn.”
Saat itulah dia sepenuhnya terjaga: pada gagasan tentang sekarat. Kini, terjaga baginya terasa seperti kejutan yang terus-menerus. Seorang pemuda bisa mati tanpa banyak memancing perhatian, pikirnya, dan aku sudah hampir mati kelaparan. Air dan prosa memang baik, mereka mengisi banyak ruang tak bernyawa, tapi air dan prosa saja tak cukup.
Kalau saja ada pekerjaan yang bisa memberinya uang, pekerjaan komersial yang paling remeh sekalipun. Kalau saja mereka mau memberinya kesempatan untuk duduk di meja sepanjang hari, menjumlahkan angka, mengurangkan, mengalikan, membagi, mungkin dia tak akan mati. Dia akan membeli makanan, segala macam makanan: hidangan lezat yang belum pernah dia cicipi—dari Norwegia, Italia, Prancis; segala jenis daging sapi, kambing, ikan, keju; anggur, ara, pir, apel, melon, dan dia akan menyembah semuanya setelah kenyang. Dia akan menaruh seikat anggur merah di piring, bersama dua buah ara hitam, sebuah pir kuning besar, dan sebutir apel hijau. Dia akan menempelkan potongan melon ke hidungnya berjam-jam. Dia akan membeli roti Prancis besar berwarna cokelat, segala macam sayuran, dan daging; dia akan membeli kehidupan.
Dari atas bukit dia memandang kota yang berdiri megah di timur, menara-menara tinggi, padat dengan manusia seperti dirinya, dan tiba-tiba dia merasa berada di luar itu semua. Dia hampir yakin tak akan pernah bisa masuk ke sana. Entah bagaimana, dia merasa telah tersesat di bumi yang salah, atau mungkin di zaman yang salah, dan kini seorang pemuda berumur dua puluh dua tahun akan dikeluarkan untuk selamanya dari sana. Pikiran itu tak membuatnya sedih. Pikirnya, satu waktu nanti aku harus menulis Surat Permohonan Izin untuk Hidup.
Dia bisa menerima gagasan tentang kematian tanpa merasa iba, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain, sambil meyakini bahwa dia masih bisa tidur satu malam lagi. Sewanya untuk satu hari sudah dibayar; masih ada satu esok lagi. Setelah itu, dia mungkin akan bergabung dengan para gelandangan lain. Mungkin dia akan mengunjungi Bala Keselamatan—bernyanyi untuk Tuhan dan Yesus (yang tak menyayangi jiwaku), diselamatkan, makan dan tidur. Tapi dia tahu dia tak akan melakukannya. Apa pun selain itu akan lebih baik.
Melayang di udara dengan trapeze terbang, pikirannya bersenandung. Menggelikan, sungguh lucu. Sebuah ayunan, trapeze, menuju Tuhan, atau menuju kehampaan, ayunan terbang menuju keabadian; dia berdoa dengan tenang agar diberi kekuatan untuk melakukan penerbangan itu secara anggun.
“Aku punya satu sen,” katanya. “Koin Amerika. Malam nanti aku akan memolesnya hingga berkilau seperti matahari, dan aku akan mempelajari kata-katanya.”
Kini dia berjalan di tengah kota, di antara manusia yang hidup. Ada satu dua tempat untuk dituju. Dia melihat bayangannya di kaca etalase toko dan kecewa dengan penampilannya. Dia tak terlihat sekuat yang dia rasakan; dia terlihat rapuh di setiap bagian tubuhnya—leher, bahu, lengan, badan, lutut. “Tak bisa begini,” katanya, dan dengan susah payah dia merapikan seluruh bagian dirinya yang kendur, menegangkannya, menegakkannya, dan membusung-busungkan dirinya agar tampak tegap dan kokoh.
Dia melewati banyak rumah makan dengan disiplin keras, menolak bahkan untuk sekadar melirik ke dalamnya, dan akhirnya tiba di sebuah gedung dan masuk ke sana. Dia naik lift ke lantai tujuh, berjalan menyusuri lorong, dan membuka pintu menuju kantor biro tenaga kerja. Di dalam sudah ada dua lusin pemuda lain; dia memilih berdiri di sudut menunggu gilirannya diwawancarai. Lama kemudian dia mendapatkan kehormatan besar itu dan ditanyai oleh seorang nona kurus, linglung, berumur lima puluh tahun.
“Sekarang ceritakan,” kata nona itu, “apa yang bisa kamu lakukan.”
Dia gugup. “Saya bisa menulis,” katanya dengan nada menyedihkan.
“Maksudmu tulisan tanganmu bagus? Begitu?” kata perempuan tua itu, terdengar tak sabar.
“Ya… begitu,” jawabnya. “Tapi maksud saya, saya bisa menulis.”
“Menulis apa?” tanya si nona, hampir dengan marah.
“Prosa,” katanya, simpel saja.
Ada kebisuan sejenak. Akhirnya perempuan itu berkata:
“Apa kamu bisa menggunakan mesin tik?”
“Tentu.”
“Baiklah, kami sudah punya alamatmu; kami akan menghubungimu. Tidak ada apa pun pagi ini, tidak ada sama sekali.”
Hal serupa terulang di biro lain, hanya saja kali ini dia ditanyai oleh seorang pemuda sombong berwajah mirip babi. Dari biro-biro itu dia pergi ke toko swalayan besar: barang-barangnya terlihat congkak, sedikit menghina dirinya, dan akhirnya ada kabar bahwa pekerjaan tidak tersedia. Dia tidak merasa kecewa, dan anehnya, bahkan tak merasa dirinya benar-benar terlibat dengan semua kebodohan itu. Dia pemuda yang hidup dan membutuhkan uang agar bisa terus hidup, dan satu-satunya cara mendapatkannya adalah bekerja; tetapi pekerjaan tak ada. Itulah persoalan abstrak yang dia coba pecahkan untuk kali terakhir. Sekarang dia senang karena perkara itu sudah selesai.
Dia mulai melihat arah hidupnya secara lebih pasti. Kecuali untuk saat-saat tertentu, hidupnya sebagian besar tanpa seni; tetapi kini, di detik-detik terakhir, dia berniat agar setidaknya segala sesuatunya menjadi lebih jernih.
Dia melewati banyak toko dan rumah makan dalam perjalanannya ke Y.M.C.A., tempat dia mengambil kertas dan tinta dan mulai menulis Surat Permohonan. Satu jam dia menulis, dan tiba-tiba, karena udara pengap dan perut lapar, dia merasa lemas. Dia merasa seolah sedang berenang menjauhi dirinya sendiri dengan kayuhan besar, dan dia buru-buru meninggalkan gedung itu. Di Civic Center Park, di seberang gedung Perpustakaan Umum, dia minum hampir satu liter air dan merasa segar kembali. Seorang lelaki tua berdiri di tengah jalan bata, dikerumuni camar, merpati, dan robin. Orang itu mengambil segenggam remah roti dari kantong kertas besar dan melemparkannya ke burung-burung dengan gerakan gagah.
Dia sempat berpikir untuk meminta sedikit remah itu, tetapi dia tak mengizinkan pikirannya mendekati kesadaran semacam itu; dia masuk ke Perpustakaan Umum dan selama satu jam membaca Proust, lalu, ketika merasa kembali berenang menjauh, dia bergegas keluar. Dia minum lagi di pancuran taman, dan memulai perjalanan panjang menuju kamarnya.
“Aku akan pergi tidur lagi,” katanya. “Tak ada hal lain yang bisa dilakukan.” Dia tahu kini bahwa dia terlalu lelah dan lemah untuk berpura-pura bahwa dia baik-baik saja, namun pikirannya entah bagaimana masih sangat lincah. Pikiran itu, seperti makhluk terpisah, terus menggumamkan lelucon lancang tentang penderitaan fisiknya.
Dia tiba di kamarnya sore dan segera membuat kopi di atas kompor gas kecil. Tak ada susu di kaleng, dan setengah pon gula yang dibelinya sepekan lalu telah habis. Dia meminum secangkir cairan hitam panas itu sambil duduk di ranjang dan tersenyum.
Dari Y.M.C.A. dia mencuri selusin lembar kertas surat yang akan dia gunakan untuk menulis, namun kini ia berpikir bahwa menulis adalah urusan menjijikkan. Tak ada lagi yang perlu disampaikan. Dia menggosok keping uang logam yang ditemukannya pagi tadi, dan tindakan konyol itu entah bagaimana memberinya luapan kesenangan.
Tak ada uang Amerika yang bisa digosok hingga berkilau seindah satu sen. Berapa banyak koin seperti itu yang dia perlukan untuk terus hidup? Bukankah ada sesuatu yang bisa dijual? Dia memandang ke sekeliling kamarnya. Tidak. Jam tangannya sudah hilang; begitu pula buku-bukunya. Semua buku bagus itu, sembilan buah, dia jual delapan puluh lima sen. Dia merasa hina telah berpisah dari buku-bukunya. Setelan terbaiknya sudah ia jual dua dolar, tapi itu tidak apa-apa. Dia sama sekali tak peduli pada pakaian. Tapi buku. Itu masalah lain. Dia sangat marah memikirkan tidak adanya penghormatan bagi orang yang menulis.
Dia menaruh koin yang berkilau itu di atas meja, menatapnya dengan kegembiraan seorang pria kikir. “Betapa manis senyumnya,” katanya. Tanpa benar-benar membacanya, dia melihat kata-kata E Pluribus Unum One Cent United States of America, dan ketika membalikkan koin itu, dia melihat Lincoln dan tulisan In God We Trust Liberty 1923. “Betapa indahnya,” katanya.
Dia mulai mengantuk dan merasakan sakit mengerikan merayap di darahnya, rasa mual dan hancur. Dengan perasaan bingung, dia berdiri di samping ranjang dan berpikir tak ada yang bisa dilakukan selain tidur.
Dia sudah merasakan dirinya melangkah jauh melalui cairan bumi dan berenang menuju awal mula. Dia jatuh tengkurap di ranjang, berkata pelan, “Seharusnya kuberikan koin ini kepada seorang anak. Dengan satu sen seorang anak bisa membeli banyak hal.”
Lalu secara cepat dan rapi, dan dengan keluwesan akrobatik seorang pemuda di trapeze, dia meninggalkan tubuhnya. Untuk satu momen yang abadi, dia sekaligus menjadi apa saja: burung, ikan, hewan pengerat, reptil, dan manusia. Di hadapannya ada lautan huruf berombak tanpa akhir dan kelam. Kota terbakar. Kerumunan menggila. Bumi berputar menjauh, dan menyadari bahwa dia telah melakukannya, dia mengarahkan wajahnya yang hilang ke langit kosong dan menjadi tak bermimpi, tak hidup, sempurna.[]
*) Diterjemahkan oleh A.S. Laksana, dari “The Daring Young Man on the Flying Trapeze”, dalam kumpulan cerpen pertama William Saroyan, The Daring Young Man on the Flying Trapeze and Other Stories (1934).

William Saroyan lahir pada 31 Agustus 1908 di Fresno, California, anak keempat dari pasangan imigran Armenia dari Bitlis, kota kuno di sebelah timur Anatolia, Kekaisaran Usmani. Ayahnya meninggal ketika ia berusia tiga tahun, ibunya harus bekerja sebagai buruh kasar di San Francisco, Saroyan dan ketiga saudaranya ditempatkan selama lima tahun di panti asuhan di Oakland. Keluarga ini bersatu kembali di Fresno pada 1916.
Pendidikannya buruk. Ia meninggalkan sekolah menengah pada 1926 tanpa lulus. Pada usia dua belas ia mulai tertarik menulis setelah membaca cerita pendek Guy de Maupassant berjudul “The Bell”. Karier menulisnya dimulai pada 1934 dengan menerbitkan cerpen-cerpen di majalah Story, yang kemudian dibukukan dalam The Daring Young Man on the Flying Trapeze and Other Stories, sebuah buku yang langsung menjadi bestseller dan menandai kedatangannya sebagai sensasi sastra Amerika.
Karya-karyanya penuh humor, optimisme, dan ironi terhadap kemiskinan di masa Depresi Besar, merefleksikan kehidupan imigran dan akar Armenianya. Kurt Vonnegut memuji gaya minimalisnya dan menyebutnya pelopor. Pada 2008, sebuah monumen didirikan untuk menghormati Saroyan di Mashtots Avenue di Yerevan, Armenia, dan pada 2014, dewan kota Bitlis menyetujui penggantian nama lima jalan di bagian bersejarah kota di Turki Tenggara, salah satu dari 5 jalan itu berganti nama menjadi Jalan William Saroyan.

Leave a Reply