Julian Barnes
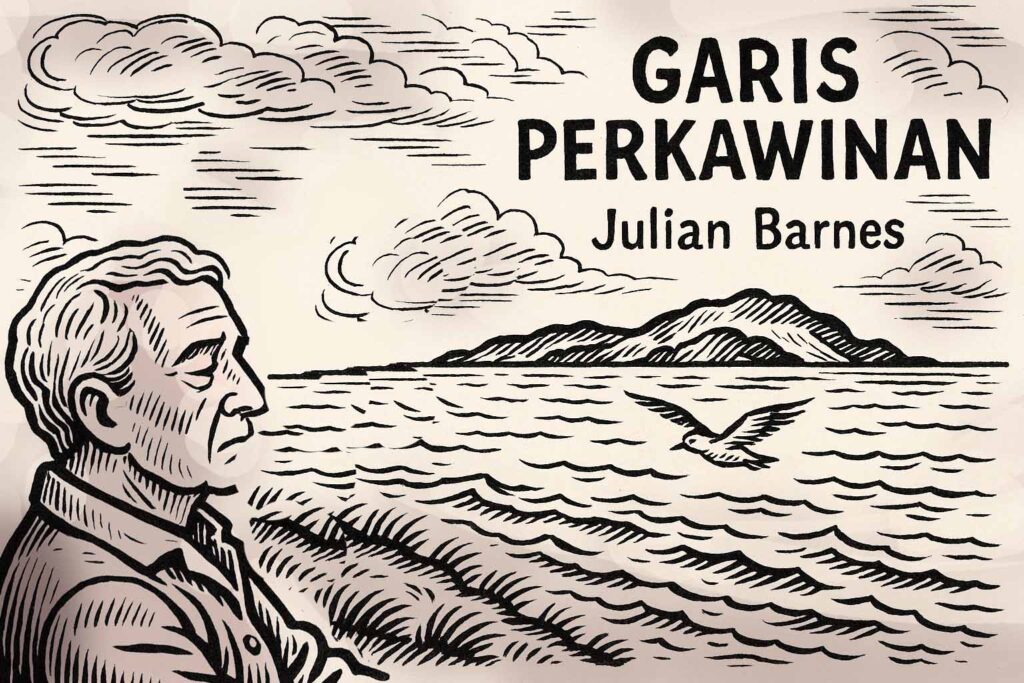
Pesawat Twin Otter itu hanya terisi separuh ketika lepas landas dari Glasgow: beberapa penduduk pulau yang kembali dari daratan, ditambah beberapa wisatawan akhir pekan di awal musim yang membawa sepatu hiking dan ransel. Hampir satu jam mereka terbang di atas bentang awan yang terlihat seperti otak yang bergerak. Lalu pesawat mulai merendah, dan tepi-tepi pulau yang bergerigi tampak di bawah mereka.
Ia selalu menyukai momen itu. Leher tanjung yang menjorok, pantai Atlantik yang panjang di Traigh Eais, bungalo putih besar yang selalu mereka lintasi, lalu berbelok halus di atas pulau kecil Orosay, dan akhirnya mendarat di hamparan datar berkilat di Traigh Mhòr. Di bulan-bulan musim panas, biasanya selalu ada suara keras dari penumpang asal daratan, mungkin berniat memukau kekasihnya, mencoba mengalahkan deru baling-baling, “Satu-satunya di dunia, pendaratan pesawat komersial di pantai!” Namun, setelah bertahun-tahun, ia bisa memakluminya. Itu semua sudah menjadi bagian yang lumrah dalam setiap perjalanan ke tempat ini.
Mereka mendarat keras di pantai kerang, dan air memercik di antara sayap-sayap saat pesawat melaju melewati genangan dangkal. Lalu pesawat berbelok menyerong ke arah bangunan terminal kecil, dan semenit kemudian mereka menuruni tangga logam reyot ke pantai. Sebuah traktor dengan gerobak datar sudah menunggu, siap mengangkut bagasi mereka sejauh belasan meter menuju lempengan beton lembap yang berfungsi sebagai karusel. Mereka, bagasi mereka: ia tahu ia harus mulai membiasakan diri dengan kata ganti orang tunggal. Inilah tata bahasa hidupnya mulai sekarang.
Calum sudah menunggunya, memandang dari bahu, melihat-lihat penumpang lain. Sosok yang sama, lelaki bertubuh kecil berambut kelabu berjaket hijau, yang selalu menjemput mereka setiap tahun. Karena Calum adalah Calum, dia tidak bertanya; dia menunggu. Mereka sudah saling kenal, dalam semacam keakraban formal, selama dua puluh tahun atau lebih. Kini rutinitas itu, pengulangan itu, dan apa saja yang dikandungnya, telah terputus.
Saat mobil van melaju pelan di jalanan sempit satu jalur, menepi setiap kali berpapasan, ia menceritakan kepada Calum kisah yang sudah terlalu sering ia ulang. Kelelahan mendadak, pusing, tes darah, hasil pemindaian, rumah sakit, rumah sakit lagi, lalu rumah perawatan. Kemendadakannya, prosesnya, tahap-tahap yang tak kenal ampun. Ia menceritakan semuanya tanpa air mata, dengan suara netral, seolah-olah itu terjadi pada orang lain. Itu satu-satunya cara yang ia tahu sejauh ini.
Di depan pondok batu gelap, Calum menarik rem tangan. “Semoga damai jiwanya,” ia berkata pelan dan mengambil alih tas besar itu.
Kali pertama mereka datang ke pulau ini, mereka belum menikah. Kekasihnya mengenakan cincin kawin sebagai bentuk kamuflase terhadap… apa?—bayangan mereka sendiri tentang moralitas orang pulau? Itu membuat mereka merasa lebih unggul dan sekaligus lebih munafik. Kamar mereka di penginapan Calum and Flora bercat putih, dengan sisa hujan mengering di jendela, dan pemandangan ke arah padang rumput di lereng tajam Beinn Mhartainn. Pada malam pertama, mereka mendapati ranjang yang berderit nyaring setiap kali ada gerak berlebihan dibandingkan sekadar gerak minimum yang diperlukan untuk pembuahan. Mereka menjadi serba salah. Seks pulau, kata mereka sambil menertawai diri sendiri.
Ia membeli teropong baru khusus untuk perjalanan itu. Di pedalaman ada burung lark dan twite, wheatear dan wagtail. Di tepi laut ada plover dan pipit bercincin. Tapi yang paling ia sukai adalah burung laut—kormoran dan gannet, shag dan fulmar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam dengan celana basah di tebing, jempol dan jari tengah memutar fokus untuk menangkap gerak berputar mereka saat menukik dan kebebasan mereka saat melayang. Fulmar menjadi kesayangannya. Burung itu hidup selamanya di laut, datang ke daratan hanya untuk bersarang. Mereka bertelur satu, membesarkan anak, lalu kembali ke laut, mengapung di atas ombak, naik ke udara mengikuti gelombang, menjadi dirinya sendiri.
Kekasihnya lebih menyukai bunga daripada burung. Sea pink, yellow rattle, purple vetch, flag iris. Ada satu yang, ia ingat, disebut self-heal. Sejauh itu saja pengetahuan dan ingatannya. Kekasihnya tak pernah memetik bunga satu pun, di sini atau di tempat-tempat lain. Memetik bunga berarti mempercepat kematian tanaman itu, katanya. Dia benci melihat vas bunga. Di rumah sakit, para pasien lain, yang melihat mejanya kosong di samping ranjang, mengira teman-temannya tak peduli, dan mencoba memberinya sisa buket mereka. Begitu terus sampai dia dipindahkan ke kamar sendiri, dan masalah itu pun selesai.
Tahun pertama itu, Calum membawa mereka keliling pulau. Suatu sore, di pantai tempat Calum biasa menggali kerang pisau, ia memalingkan wajah dari mereka dan berkata, hampir seperti kepada laut, “Kakek-nenek saya menikah hanya dengan pernyataan. Dulu begitu saja sudah cukup. Persetujuan dan pernyataan. Orang menikah ketika bulan sedang membesar dan pasang sedang naik—agar diberkati keberuntungan. Setelah upacara, akan disediakan kasur kasar di lantai gudang di pekarangan belakang. Untuk malam pertama. Itu berarti, kamu memulai pernikahan dalam keadaan rendah hati.”
“Oh, itu indah sekali, Calum,” kata kekasihnya. Tapi ia merasa ucapan itu sebagai teguran—terhadap sopan santun Inggris mereka, keangkuhan mereka, kebohongan diam-diam mereka.
*
Tahun kedua, mereka kembali beberapa minggu setelah menikah. Mereka ingin mengabarkan itu kepada semua orang yang mereka temui; tetapi di tempat ini mereka tak bisa. Mungkin itu justru baik bagi mereka—menjadi tolol karena terlalu bahagia, namun dipaksa diam. Mungkin itu cara mereka sendiri untuk memulai pernikahan dalam keadaan rendah hati.
Namun ia merasa bahwa Calum dan Flora sudah menebak. Tak sulit, tentu saja, melihat pakaian baru mereka dan senyum bodoh di wajah mereka. Pada malam pertama, Calum menuangkan wiski dari botol tanpa label. Ia punya banyak botol semacam itu. Di pulau ini, lebih banyak wiski yang diminum daripada yang dijual.
*
Flora mengeluarkan dari laci sepotong sweater tua milik kakeknya. Ia membentangkannya di meja dapur dan menggosok permukaannya dengan telapak tangan. Dulu, katanya, perempuan di pulau-pulau ini biasa bercerita melalui rajutan mereka. Pola pada sweater itu menunjukkan bahwa kakeknya berasal dari Eriskay, sementara detail dan hiasannya bercerita tentang memancing dan keyakinan mereka, tentang laut dan pasir. Dan deretan zigzag di bagian bahu—yang ini, lihat—melambangkan naik-turunnya perkawinan. Itulah, secara harfiah, garis perkawinan.
Zigzag. Seperti pasangan muda mana pun yang baru menikah, mereka saling memandang dengan kepercayaan diri yang naif bahwa bagi mereka tidak akan ada garis menurun—atau setidaknya, tidak seperti yang dialami orang tua mereka, atau teman-teman yang sudah membuat kesalahan tolol yang mudah ditebak. Mereka akan berbeda; mereka akan berbeda dari siapa pun yang pernah menikah sebelumnya.
“Ceritakan kepada mereka tentang kancing-kancingnya, Flora,” kata Calum.
Pola pada sweater menunjukkan dari pulau mana pemiliknya berasal; sedangkan kancing di bagian leher menunjukkan dari keluarga mana ia datang. Seperti berjalan dengan kode pos pribadi di tubuhmu, pikirnya.
Beberapa hari kemudian, ia berkata kepada Calum, “Aku berharap semua orang masih mengenakan sweater seperti itu.” Ia sendiri tak punya rasa kepemilikan atas tradisi apa pun, tapi ia senang melihat orang lain menunjukkannya.
“Sweater itu sangat berguna,” jawab Calum. “Seringkali orang yang tenggelam langsung bisa dikenali dari sweaternya. Juga dari kancingnya. Orang tahu siapa dia.”
“Aku tak pernah terpikir soal itu.”
“Ya, memang tak ada alasan bagimu untuk tahu. Atau untuk memikirkannya.”
Ada saat ia merasa ini tempat paling jauh yang pernah ia datangi. Penduduk pulau kebetulan berbahasa sama dengannya, tapi itu sekadar kebetulan geografis yang aneh.
*
Kali ini, Calum dan Flora memperlakukannya sebagaimana yang selalu mereka lakukan: dengan kehalusan dan kerendahan hati yang sama, yang secara bodoh, jenis kebodohan Inggris, pernah ia tafsirkan sebagai sikap tunduk. Mereka tidak menghamba, atau memamerkan simpati. Hanya sentuhan di bahu, sepiring suguhan, sepatah komentar tentang cuaca.
Setiap pagi, Flora memberinya sepotong sandwich yang dibungkus kertas minyak, sepotong keju, dan sebutir apel. Ia akan berangkat melintasi padang rumput dan mendaki Beinn Mhartainn. Ia memaksa diri naik sampai puncak, tempat ia bisa melihat seluruh pulau dan tepiannya yang seperti gerigi, tempat ia bisa benar-benar merasa sendiri. Lalu, dengan teropong di tangan, ia menuju tebing-tebing karang dan burung-burung laut.
Pernah Calum bercerita bahwa di beberapa pulau, beberapa generasi lalu, orang membuat minyak lampu dari burung fulmar. Dan selama dua puluh tahun lebih ia menyembunyikan hal itu dari istrinya. Sepanjang tahun tak pernah ia memikirkan hal ini. Namun, setiap kali mereka datang ke pulau ini, ia akan berkata dalam hati, aku tak boleh memberi tahu dia apa yang mereka lakukan terhadap burung-burung fulmar itu.
*
Musim panas itu, istrinya hampir meninggalkannya (atau justru ia yang hampir meninggalkan istrinya?—dari jarak ini, ia tak tahu lagi) saat ia pergi mencari kerang bersama Calum. Istrinya membiarkan mereka bersenang-senang dengan kegiatan itu dan memilih berjalan-jalan sendiri di sepanjang garis lembap pantai saat laut sedang surut. Di sini, yang kerikilnya nyaris seukuran butir pasir, istrinya suka mencari pecahan kaca berwarna—potongan-potongan kecil dari botol yang pecah, yang dikikis dan dihaluskan oleh air dan waktu. Bertahun-tahun ia mengamati cara istrinya melangkah membungkuk, berjongkok penuh rasa ingin tahu, cara dia memilih, membuang, mengumpulkan pecahan-pecahan kaca dalam telapak tangan kirinya yang dicekungkan.
Calum menjelaskan cara mencari kerang pisau—menemukan lekukan di pasir, menuang sedikit garam ke dalamnya, dan menunggu kerang itu muncul beberapa senti dari lubangnya. Ia memakai sarung tangan oven yang tebal di tangan kiri untuk melindungi diri dari tepi cangkang yang tajam. Harus cepat, katanya, tangkap sebelum kerang itu menghilang lagi.
Meski Calum berpengalaman, kebanyakan kerang tak muncul, dan mereka berpindah ke lekukan pasir berikutnya. Dari sudut matanya, ia melihat istrinya berjalan makin jauh di sepanjang pantai, memunggunginya, hanyut pada kegiatannya sendiri, tanpa memikirkan dirinya, sang suami, sama sekali.
Saat ia memberikan garam lagi ke Calum, dan melihat sarung tangan oven itu bersiaga, ia tiba-tiba berkata, sebagai sesama lelaki, “Agak mirip pernikahan, ya?”
Calum mengerutkan dahi. “Apa maksudmu?”
“Oh, menunggu sesuatu keluar dari pasir. Lalu ternyata tidak ada apa-apa, atau malah sesuatu yang melukai tangan kita kalau kita tak hati-hati benar.”
Itu ucapan bodoh. Bodoh karena ia tak sungguh-sungguh bermaksud begitu, dan lebih bodoh lagi karena terdengar lancang. Kebisuan setelahnya mengabarkan bahwa Calum menganggap omongan itu menyinggung—bagi dirinya, bagi Flora, bagi orang-orang pulau pada umumnya.
*
Setiap hari ia berjalan, dan setiap hari hujan lembut meresap ke dalam tubuhnya. Ia memakan sandwich yang lembek dan memandangi burung-burung fulmar meluncur di atas laut. Ia berjalan sampai ke Greian Head dan menatap ke bawah, ke bebatuan datar tempat kawanan anjing laut suka berkumpul. Suatu tahun, mereka pernah menyaksikan seekor anjing berenang jauh dari pantai, mengusir anjing-anjing laut itu, lalu berjingkrak di atas batu seperti tuan tanah baru. Tahun ini tak ada anjing.
Di lereng curam Greian terdapat bagian dari lapangan golf yang tidak masuk akal; tahun demi tahun tak pernah mereka melihat satu pun pegolf. Ada lapangan hijau kecil berbentuk lingkaran yang dikelilingi pagar kayu untuk menghalangi sapi-sapi. Pernah, di dekat situ, sekelompok lembu muda tiba-tiba menyerbu ke arah mereka, membuat istrinya ketakutan setengah mati. Ia berdiri tegak, melambaikan tangan sekuat tenaga, spontan berteriak menyebut nama-nama para pemimpin politik yang paling ia benci, dan entah bagaimana kawanan lembu itu menjadi tenang. Tahun ini tak ada lembu yang terlihat, dan ia merindukan mereka. Ia pikir mereka pasti sudah lama disembelih.
Ia teringat seorang petani di Vatersay yang pernah bercerita tentang lazy beds—cara malas bertanam. Kamu potong sebidang rumput, letakkan kentang di tanah yang terbuka, lalu kembalikan rumput itu menutupi kentang—begitu saja. Waktu, hujan, dan hangatnya matahari akan mengurus sisanya. Lazy beds—ia bisa melihat istrinya tertawa kepadanya, menebak isi pikirannya, lalu berkata ini jenis berkebun yang cocok untukmu, kan? Ia teringat mata istrinya yang berkilau seperti pecahan-pecahan kaca yang dulu sering dia kumpulkan di telapak tangannya.
*
Pagi terakhir, Calum mengantarnya kembali ke Traigh Mhòr dengan van. Para politisi sedang menjanjikan landasan udara baru agar pesawat modern bisa mendarat. Ada pembicaraan tentang pengembangan wisata dan peremajaan pulau, disertai peringatan tentang biaya subsidi yang kian besar. Calum tidak menginginkan semua itu. Ia juga. Ia membutuhkan pulau ini tetap begini, tak berubah selama mungkin. Ia tak akan kembali jika pesawat jet mulai mendarat di landasan aspal.
Ia menitipkan tas besarnya di loket dan mereka keluar. Menyandar di dinding rendah, Calum menyalakan rokok. Mereka memandangi pasir yang bergelombang di pantai kerang itu. Awan menggantung rendah, kantong arah angin tak bergerak.
“Ini untukmu,” kata Calum sambil menyerahkan setengah lusin kartu pos. Mungkin ia baru membelinya di kafe. Pemandangan pulau, pantai, padang rumput; satu bergambar pesawat yang akan membawanya pergi.
“Tapi…”
“Kamu akan membutuhkan kenangan.”
Beberapa menit kemudian, Twin Otter itu lepas landas lurus melintasi Orosay dan laut terbuka. Pulau sudah lenyap dari pandangan sebelum dunia di bawah sana tertutup awan. Dalam selubung awan-awan, ia memikirkan garis perkawinan dan kancing-kancing; tentang kerang pisau dan seks pulau; tentang lembu yang tak ada lagi dan burung fulmar yang dijadikan minyak; dan berakhir dengan air mata. Calum tahu bahwa ia tak akan kembali. Tapi air matanya bukan karena itu, bukan pula untuk dirinya, atau bahkan untuk istrinya, atau untuk kenangan mereka. Itu air mata untuk kebodohannya sendiri. Untuk kesombongannya juga.
Ia pikir ia akan bisa menangkap lagi masa lalu, dan mengucapkan selamat tinggal. Ia pikir duka bisa diredakan, atau jika tak bisa diredakan, setidaknya bisa dipercepat, didorong sedikit lajunya, dengan kembali ke tempat mereka pernah bahagia. Tapi bukan ia yang mengendalikan duka. Dukalah yang mengendalikannya. Dan di bulan-bulan serta tahun-tahun mendatang, ia tahu duka akan mengajarinya banyak hal lain pula. Ini baru yang pertama.[]
*) Diterjemahkan oleh A.S. Laksana dari “Marriage Lines”, dalam buku That Glimpse of Truth: 100 of The Finest Short Stories Ever Written.

Julian Patrick Barnes lahir pada 19 Januari 1946 di Leicester, Inggris, dari orang tua yang keduanya guru bahasa Prancis. Ia lulus dari studi bahasa modern di Magdalen College, Oxford, dengan predikat honors pada 1968, dan memulai karier sebagai leksikografer untuk suplemen Oxford English Dictionary selama tiga tahun, sebelum beralih menjadi penulis resensi dan editor sastra untuk majalah seperti New Statesman dan New Review pada 1977. Dari 1979 hingga 1986, ia juga menjadi kritikus televisi untuk The Observer.
Novel pertamanya adalah Metroland (1980), disusul kemudian dengan novel-novel inovatif Flaubert’s Parrot (1984), yang menjadi terobosan dan masuk nominasi Booker Prize, serta A History of the World in 10½ Chapters (1989). Ia juga menulis empat novel kriminal dengan nama samaran Dan Kavanagh. Pada 2011, novelnya The Sense of an Ending (2011) memenangi Man Booker Prize setelah tiga kali nominasi sebelumnya.
Barnes seorang Francophile yang sering mengeksplorasi hubungan Inggris-Prancis. Ia menikah dengan agen sastra Pat Kavanagh pada 1979; pernikahan mereka berlangsung hingga Kavanagh meninggal akibat tumor otak pada 2008, pengalaman yang ia tuangkan dalam memoar Levels of Life (2013). Julian Barnes adalah salah satu penulis Inggris kontemporer yang inovatif, dengan tema obsesi terhadap masa lalu dan identitas.
Dari pemerintah Prancis, ia menerima gelar “Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres”, penghargaan tertinggi di bidang seni dan sastra, yang dimulai penganugerahannya pada 1957 oleh Menteri Kebudayaan Prancis André Malraux.

Leave a Reply